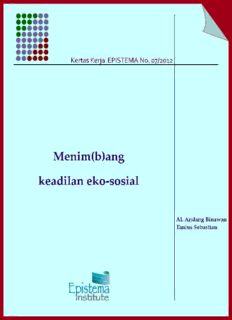
Menim(b)ang keadilan eko-sosial PDF
Preview Menim(b)ang keadilan eko-sosial
Kertas kerja EPISTEMA No. 07/2012 Menim(b)ang keadilan eko‐sosial Al. Andang Binawan Tanius Sebastian 2012 Tentang Kertas Kerja Epistema Paper‐paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil‐hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, research fellow dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper‐paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian sosio‐legal terhadap hak‐hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim. Saran pengutipan: Binawan, Al. Andang, Tanius Sebastian. Menim(b)ang keadilan eko‐sosial, Kertas Kerja Epistema No.07/2012, Jakarta: Epistema Institute (http://epistema.or.id/menimang‐keadilan‐ekososial/). EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggandaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial. Paper‐paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui [email protected] atau [email protected]. Penata letak : Andi Sandhi Epistema Institute Jalan Jati Mulya IV No.23 Jakarta 12540 Telepon : 021‐78832167 Faksimile : 021‐7823957 E‐mail : [email protected] Website : www.epistema.or.id 2 PENGANTAR KE PERMASALAHAN Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kesempatan konperensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa‐bangsa tentang pembangunan berkelanjutan (KTT Rio+20), 21 Juni 2012, menyampaikan gagasan lebih rinci tentang ekonomi hijau yang sudah mulai dikembangkan oleh UNEP (United Nations Environment Programme) sejak tahun 2008. Ada hal yang menarik dari gagasan itu, yaitu terutama dalam upaya mengakomodasi dengan lebih baik keprihatinan akan kerusakan lingkungan hidup. Dengan kata lain, ekonomi hijau berusaha merumuskan paradigma baru ekonomi yang berperspektif ekologis, yang mau mengubah paradigma dari ‘greedy economy’ ke ‘green economy.’ Bahwa hal itu masih berupa konsep, dan masih banyak kritik,1 itu perkara lain, dan sejauh mana bisa diterapkan, tidak akan dibahas dalam paparan ini. Yang mau digarisbawahi disini adalah bahwa munculnya gagasan ekonomi hijau tentu tidak muncul tiba‐tiba. Ada nuansa kegalauan yang kental dalam konsep itu, terutama dalam menghadapi ketegangan ekonomi dan ekologi. Di satu sisi manusia dan/atau sebuah bangsa mau makmur secara ekonomis, yang dalam kenyataan ternyata merusak alam, dan di lain pihak tidak ingin mendapatkan alam yang rusak. Kegalauan ini sudah lama disadari manusia, meski baru menyeruak menjadi keprihatinan internasional pada tahun 1972 dengan diselenggarakannya Konperensi Perserikatan Bangsa‐bangsa tentang lingkungan hidup. Dua puluh tahun kemudian, keprihatinan itu masih muncul, dan denyutnya terasa dalam Earth Summit 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Keprihatinan itu mendorong munculnya gagasan tentang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Hanya, masih tampak bagaimana paradigm pembangunan dan ekonomi masih dominan. Empat puluh tahun setelah Stockholm, atau dua puluh tahun setelah Rio, gagasan tentang ekonomi hijau, sebagai modifikasi lebih jauh dari pembangunan berkelanjutan ramai dibicarakan. Sekali lagi, gagasannya cukup menarik, meski tidak tanpa kelemahan, dan sekaligus tidak menutupi kegalauan dunia internasional terkait dengan dilema antara ekonomi dan ekologi. 1 Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), yang mempunyai banyak data tentang kerusakan lingkungan akibat pertambangan, adalah salah satu pihak yang mengritik gagasan itu. Lihat siaran pers‐nya tertanggal 29 Juni 2012 yang berjudul: “Green Economy: Mimpi Buruk Masa Depan Indonesia.” Demikian juga Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), meski bukan pernyataan resmi, melalui salah satu aktivisnya, Khalisah Khalid, menulis di harian Kompas 21 Juni 2012 hal. 6, “”Gelapnya” Ekonomi Hijau.” 3 Untuk Indonesia, situasinya menjadi tampak lebih rumit dan makin membuat galau. Hanya beberapa hari sebelum presiden RI berpidato di Rio de Janeiro, The Fund for Peace, sebuah lembaga penelitian nirlaba independen dari Washington, DC, Amerika Serikat, mengeluarkan hasil penelitian mereka tentang indeks negara gagal. Disebutkan bahwa Indonesia ada di peringkat 63 dari 178 negara di dunia. Artinya, dengan indeks 80,6 (rata‐ rata dari 12 indikator, termasuk kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum) Indonesia sudah di ambang bahaya masuk kategori negara gagal! Dalam laporan itu, terkait dengan masalah penduduk dan lingkungan, dikatakan bahwa “Indonesia’s Demographic Pressures score remains high due to water security issues, land degradation, and displacement due to environmental pressures.” Dalam hal ini, dengan skor 7,4, Indonesia ada di peringkat 59, yang berarti masih dalam kategori ‘mendapat peringatan’ (warning). Sementara itu, yang dimaksud dengan Demographic Pressures oleh lembaga ini adalah “Pressures on the population such as disease and natural disasters make it difficult for the government to protect its citizens or demonstrate a lack of capacity of will. Includes pressures and measures related to natural disasters, disease, environment, pollution, food scarcity, malnutrition, water scarcity, population growth, youth bulge and mortality.”2 Laporan penelitian ini, meski buru‐buru dibantah oleh banyak pihak, khususnya pemerintah Indonesia, tetap bisa memberi indikasi kegagalan negara Indonesia menjamin keadilan sosial untuk rakyatnya. Meski tidak sangat eksplisit dikatakan, bisa dibayangkan bahwa kegagalan itu juga terkait dengan kerusakan lingkungan di bumi Indonesia, baik karena pembabatan hutan, pembuatan perkebunan monokultur besar‐besaran, eksploitasi pertambangan yang merusak, juga makin langkanya air, terutama air bersih, bahkan langkanya udara bersih di perkotaan. Keadilan sosial, yang nota bene sudah diamanatkan dalam Pancasila, dalam hal ini, erat kaitannya dengan masalah ekologis. Menjadi pertanyaan sekarang, apa sebab kegagalan itu. Tentu, salah satu faktor penting kegagalan itu adalah penegakan hukum yang sangat lemah di Indonesia. Laporan The Fund for Peace tadi, dalam 2 Tentang laporan lengkap indeks itu, lihat: http://www.fundforpeace.org/global/?q=node/242. Hasil riset ini bisa dikatakan ‘sejajar’ dengan hasil riset UNDP (United Nations Development Development Programme) tentang indeks pembangunan manusia (human development index) yang menempatkan Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara yang diteliti. Faktor lingkungan memang tidak disebut secara eksplisit, tetapi dengan membaca umur harapan hidup (69,4 tahun) dan indeks kesehatan yang masih relatif rendah, cukup bisa dibaca bagaimana situasi sosial dan ekologis di Indonesia. 4 hal human rights and rule of law,3 memberi skor 6,8 yang berarti di peringkat 70. Laporan ini memang tidak cukup rinci. Yang lebih rinci tentang situasi penegakan hukum di Indonesia adalah laporan dari the World Justice Project yang meneliti situasi penegakan hukum di 66 negara. Dalam daftar Rule of Law Index 2011 yang dikeluarkan sebagai hasil penelitiannya,4 dari 66 negara itu Indonesia juga ada di tengah. Mengaitkan buruknya keadilan sosial dengan situasi penegakan hukum adalah hal yang sangat logis, mengingat cita‐cita hukum yang pertama adalah keadilan, selain ketertiban dan manfaat. Karena itu, pertanyaan lalu bisa dilanjutkan dengan mengapa penegakan hukum di Indonesia relatif buruk. Pertanyaan bisa dijawab secara politis, bisa juga secara filosofis. Mengingat bahwa tujuan penelitian ini bukan untuk menjawab persoalan praktis‐aplikatif, jawaban jenis kedua‐lah yang mau dicari. Salah satu hipotesis adalah bahwa rumusan hukum‐nya sendiri beserta para penegaknya kurang mempunyai wawasan, atau bahkan paradigma, keadilan sosial. Sehubungan dengan masalah itu, paparan ini mencoba memberi cakrawala keadilan yang lebih luas, yaitu keadilan eko‐sosial, terutama karena –seperti telah dilihat di atas‐ keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari masalah ekologis. Memang, sehubungan dengan perspektif keadilan sosial dalam kaitan dengan persoalan ekologis itu, konsep ekonomi hijau (green economy) bisa menjadi alternatif jawaban. Dalam hal ini diandaikan bahwa sumber utama ketidakadilan sosial dan ekologis adalah sistem ekonomi kapitalis dengan ideologi neoliberal. Untuk menanggapi permasalahan itulah UNEP (United Nations Environment Programme), sebagai salah satu lembaga internasional yang secara khusus memperhatikan masalah lingkungan hidup, mulai meluncurkan gagasan ini pada tahun 2008. Dalam rumusan mereka, “green economy as one that results in improved human well‐being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In its simplest expression, a green economy can 3 Terkait dengan kategori ini, yang diukur adalah: “When human rights are violated or unevenly protected, the state is failing in its ultimate responsibility. Includes pressures and measures related to press freedom, civil liberties, political freedoms, human trafficking, human prisoners, incarceration, religious persecution, torture, executions.” 4 Hasil penelitian itu bisa diunduh dari: http://worldjusticeproject.org/?q=rule‐of‐law‐index/index‐2011. 5 be thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive.”5 Meski telah dicoba diterapkan, konsep ekonomi hijau ini masih memerlukan evaluasi, baik dalam penerapan maupun dalam konsep dasarnya. Dengan kata lain, masih perlu dipertanyakan sejauh mana gagasan ini telah menampung gagasan keadilan eko‐sosial. Sebelum lebih jauh, perlulah diingat lebih dahulu bahwa keadilan adalah salah satu konsep yang terus diperdebatkan sepanjang masa, sulit dirumuskan dengan pasti, karena senantiasa mengelak. Tak satu pemikir atau filsuf pun yang berhasil membidik keadilan dengan sempurna. Tak ada satu pun rumusan konseptual yang utuh, tanpa memberi ruang pada kemungkinan kritik. Menurut Karen Lebacqz. keadilan itu cerita gajah yang diteliti oleh para peneliti buta. Setiap peneliti merasakan bagian yang berbeda – kaki, telinga, gading – sehingga masing‐masing melukiskan makhluk ini dengan cara yang berbeda‐beda pula – gemuk dan kuat, tipis dan lentur, halus dan keras. Gajah itu sendiri – sang keadilan – tidak pernah bisa dikenal seluruhnya oleh deskripsi individual manapun.6 Meski begitu hal ini telah tidak menghentikan langkah para pemikir untuk meneliti dan merumuskan makna dari keadilan. Keadilan seolah dibutuhkan, hadir, dan dirasakan secara inheren di dalam kehidupan manusia. Ungkapan Agustinus bahwa: “Tanpa keadilan, negara tidak lain hanya gerombolan perampok yang teroganisir”, misalnya, seperti mau memperlihatkan bahwa keadilan diperlukan keberadaannya di setiap kehidupan manusia. Situasi yang mendorong manusia untuk menimbang makna keadilan adalah pengalaman ketidakadilan yang dialami, baik yang dialami seorang pribadi vis‐a‐vis pribadi lain, kelompok tertentu, etnis tertentu atau bahkan sebuah bangsa. Dalam sejarah, begitu banyak peristiwa ketidakadilan itu hadir di tengah masyarakat dan dunia, sehingga ‘memaksa’ orang mencoba merumuskan makna keadilan dari pengalaman ketidakadilan, merumuskan sesuatu yang positif dari pengalaman negatif. Salah satu tonggak penting perenungan manusia dan juga bangsa‐bangsa tentang makna keadilan adalah konsep dan juga deklarasi universal hak asasi manusia (1948) dengan segala turunannya. Keadilan individu dijabarkan dalam hak‐hak sipil dan politik (terangkum 5 Lihat rumusan yang mereka cantumkan dalam website resmi UNEP, lihat: http://www.unep.org/greeneconomy/ AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx, diakses pada tanggal 4 Juli 2012 jam 18.00/. 6 Karen Lebacqz, Teori‐Teori Keadilan, terjemahan Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 1. 6 dalam International Covenant on Civil and Political Rights, 1966), dan keadilan yang lebih berwarna sosial dijabarkan dalam hak‐hak ekonomis, sosial dan budaya . (terangkum dalam International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, 1966). Kedua kategori keadilan ini biasanya disebut sebagai HAM (hak asasi manusia) generasi pertama dan kedua. Hanya saja, patut dicatat, bahwa perumusan hak‐hak asasi manusia masih bersifat minimal. Hak‐hak asasi manusia adalah keadilan minimal, baik minimal dari sisi konseptual, temporal maupun spasial. Secara konseptual, sebuah rumusan (semi) yuridis jelas mereduksi sebuah konsep filosofis. Secara temporal, sebuah rumusan selalu tertatih‐tatih mengikuti gerak jaman. Kemudian, secara spasial pun sebuah rumusan akan punya ‘bias’ budaya tertentu yang belum tentu bisa begitu saja diterapkan dalam konteks atau budaya lain. Sekarang pun wacana tentang HAM generasi ketiga terus bergulir, yang berusaha mengakomodasi hak‐hak yang terkait dengan hak komunal dan hak yang terkait dengan lingkungan hidup atau bisa dikaitkan dengan pencarian makna keadilan ekologis dan eko‐ sosial. Meski sudah bergulir cukup lama, HAM generasi tiga belum mengental dengan sebutan ‘universal.’ Di lain pihak, berbagai bentuk konvensi internasional yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dan pemanasan global sudah muncul dan diberlakukan. Selain konteks kepentingan ekonomi dan politik, yang menyulitkan belum adanya HAM generasi ketiga yang universal adalah juga masih abstrak‐nya hak‐hak itu dan makna keadilannya. Seperti disebutkan di atas, kalau ‘keadilan’ saja tak gampang dirumuskan, apalagi keadilan ekologis. Meski begitu, penelitian ini tetap mencoba menimang dan menimbang makna keadilan ekologis itu, dengan harapan bisa lebih diterapkan dalam kenyataan. Dikatakan ‘menimang dan menimbang’ karena pada dasarnya penelitian ini tidak bertujuan untuk merumuskan makna keadilan ekologis, melainkan mencoba menelusuri apa yang pernah dikatakan para pemikir, melihat unsur‐unsur pokoknya, dan mencoba menggaris‐bawahi dan memetakannya. Alur besar tulisan ini adalah menimang, menimbang dan akhirnya meminang. Maksudnya, tulisan akan diawali dengan menimang dan menimbang beberapa paham keadilan. Hal ini dilakukan dengan mencermati dan menggaris‐bawahi beberapa hal pokok dari makna keadilan yang dirumuskan beberapa pemikir. Yang dipilih adalah pandangan dari beberapa pemikir yang sering dijadikan referensi, meski dilengkapi dengan beberapa sumber lain. Dengan pengandaian bahwa keadilan ekologis terkait erat dengan keadilan 7 sosial, sebelum sampai ke keadilan ekologis, lebih dahulu keadilan sosial akan ditimang dan ditimbang, juga dengan menampilkan beberapa pemikiran. Dengan langkah itu, diharapkan unsur‐unsur penting, pendasaran filosofis maupun problematik keadilan ekologis bisa disimpulkan. Bertolak dari rangkuman umum ini, sesuai dengan status questionis (pertanyaan dasar) yang melandasi penelitian ini, bagian akhir tulisan mengusulkan untuk meminang makna keadilan eko‐sosial. Dalam hal ini jelas diandaikan bahwa esensi keadilan sesungguhnya tidak memiliki makna yang tunggal dan tetap. Ketidaktetapan dan cairnya makna keadilan ini justru yang membuat para pemikir mencurahkan segenap tenaga dan usahanya untuk mencari apa itu makna keadilan, sehingga dapat ditemukan konstelasi makna keadilan yang saling bertolak belakang di antara para pemikir, atau justru makna yang saling berdialektika. Karena itu, sebagai semacam rangkuman, akan dibuat pemetaan atas unsur‐unsur pokok dari berbagai pemikiran itu. Rangkuman akan menggarisbawahi beberapa pokok, yaitu (1) pokok masalahnya, (2) isi atau ‘apa’‐nya, (3) jangkauan dan jenisnya, (4) cara atau ‘bagaimana’nya dan terakhir (5) problematik filosofis yang ada. Pada bagian akhir, ada catatan khusus tentang keadilan eko‐sosial. Sebagai catatan umum, perlu diingat bahwa secara garis besar pemikiran tentang keadilan bisa digolongkan dalam dua aliran, yaitu aliran liberal dan aliran komunitarian. Yang pertama lebih menekankan otonomi masing‐masing individu manusia, dengan masyarakat sebagai unsure pendukung saja. Sementara itu yang kedua melihat bahwa masyarakat adalah sebuah entitas yang mutlak ada bagi pribadi‐pribadi. Artinya, keberadaan masyarakat bukan sekedar agregat atau penjumlahan keberadaan pribadi‐ pribadi itu. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini tidak akan terlalu memperhatikan perbedaan pendekatan itu. 8 I. MENIMANG KEADILAN Apa yang akan dibahas di bawah ini adalah makna keadilan menurut para pemikir atau filsuf yang terentang dari segala zaman. Banyak pemikir atau filsuf yang menyampaikan pandangannya tentang keadilan ini, tetapi tidak semua bisa dipaparkan. Dipilih beberapa di antara mereka yang dipandang bisa mewakili ragam pandangan tentang keadilan. Secara filosofis, pandangan mereka memang bersifat spekulatif‐reflektif, tapi itu semua dirangkai dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk yang hidup dalam suatu konteks peristiwa atau situasi. “Ada – yang ‐ mengada”, “Dasein – yang – hadir ‐ dalam‐ kebersamaan”, seperti yang diungkapkan oleh Martin Heidegger. Semenjak munculnya kompleksitas kehidupan bersama dalam unit polis di Yunani, mulai muncul pertanyaan: bagaimana seharusnya manusia harus bertindak sebagai warga polis “yang baik”? Inilah embrio awal atas refleksi akan apa yang disebut dengan “yang adil”. Sehubungan dengan paham keadilan ini, ada beberapa jenis pandangan. Pertama, keadilan dapat dipandang sebagai sebuah keutamaan (virtue). Pendapat ini menekankan makna bahwa keadilan adalah sebentuk virtue yang muncul dari upaya reflektif individu mengenai cara hidup yang baik dan yang sesuai dengan etika. Konsep keadilan seperti ini dapat kita temukan dari gagasan Plato. Kedua, keadilan yang dipandang sebagai keutamaan tadi tidak hanya melulu muncul dan eksis di relung pribadi masing‐masing individu, namun lebih jauh lagi, keadilan hadir pada suatu situasi dan komunitas kehidupan manusia. Keadilan di sini memiliki lingkup yang lebih luas dan merupakan cikal bakal berkembangnya ide keadilan sosial.7 Konsep keadilan seperti ini dapat kita lacak pada gagasan Aristoteles. Ketiga, gagasan keadilan tidak dipahami sebagai hasil refleksi moral filosofis yang semata‐ mata lahir dari masing‐masing pribadi manusia ataupun yang jangkauannya kolektif. Keadilan lebih dikaitkan kepada pengaturan struktur dasar kehidupan masyarakat yang terkait dengan bidang kehidupan politik, sosial, dan ekonomi.8 Yang menjadi perhatian adalah usaha untuk membentuk tatanan keseluruhan masyarakat yang berkeadilan, yang 7 Lihat: Michael Slote, “Justice as a Virtue,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/entries/justice‐virtue/#5, diakses pada 24 Maret 2012, pukul 19.03 WIB. 8 Caroline Walsh, “Rawls and Walzer on Non‐Domestic Justice,” Contemporary Political Theory, http://www.palgrave‐journals.com/cpt/journal/v6/n4/full/9300303a.html, diakses pada 24 Maret 2012, pukul 19.46 WIB. 9
Description: